Langit
seakan berjelaga. Telah masuk minggu ketiga, angkasa yang menaungi bumi bertuah
ini tertutup asap tebal. Tak ada lagi arak-arakan awan berlatar birunya langit.
Sang surya seakan bersembunyi di posisi terjauh pada lingkaran tata surya. Meninggalkan
singgasananya di pusat orbit. Beberapa menit lalu, ISPU1)
menunjukkan angka polutan 410. Telah lewat seratus sepuluh poin, kondisi udara
kota ini berada pada level berbahaya.
“Belum
ada pertanda apa-apa.”
Di
sebelah saya, Pak Roy bergumam dibalik maskernya. Meski separuh wajahnya
tertutup masker, kecemasan yang terpancar dari kedua matanya begitu kentara.
Pak Roy adalah salah satu pejabat Badan Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru.
Dan hari ini, selain saya dan Pak Roy, belasan orang dari lintas instansi berada
di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan hasil penyemaian hujan buatan.
Menurut perkiraan, hujan diprediksi akan turun beberapa hari setelah program
modifikasi cuaca dimulai.
Namun
sampai hari ini, upaya itu belum lagi menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Lebih
buruknya lagi, sudah seminggu ini bandara Sultan Syarif Kasim tutup total. Membuat
semua schedule penerbangan pesawat Cassa
yang mengangkut ton-tonan garam untuk penyemaian pun terpaksa dibatalkan.
Tadi
pagi, tim modifikasi cuaca mencoba alternatif lain dengan bantuan helikopter. Begitu
jarak pandang melampaui seribu meter, helikopter langsung bergerak menuju
titik-titik potensi pembentukan awan. Diperkirakan, jika kelembapan atmosfer
cukup memadai, maka tiga jam pasca penyemaian, langit akan bereaksi. Namun, alih-alih
dapat memancing kemurahan Tuhan untuk menurunkan butiran hujan, kadar polutan
justru terus meningkat. Meninggalkan level Sangat Tidak Sehat dan memasuki
level Berbahaya. Tiga jam sudah berada di udara terbuka, napas saya mulai
sesak, dan mata saya terasa perih. Sepertinya, masker hijau yang saya kenakan,
hanya mampu memberi perlindungan maksimal tidak lebih dari dua jam.
Ponsel
saya membunyikan pesan masuk. Nama Bim Bim, partner
kerja saya muncul di layar. Kabar duka,
Ret. Yani baru saja meninggal.
Saya
terhenyak. Sebuah godam seakan baru saja dihantamkan ke dada saya dan tak
sempat saya menangkisnya. Yani. Dalam sekejap, bayangan wajah bocah lima tahun
itu berkelebat. Wajahnya yang tersengal kebiruan saat dilarikan ke rumah sakit
kemarin sore. Bocah itu mengidap asthma bawaan sejak lahir. Rumahnya persis
bersebelahan kost-kostan saya. Dan menurut ibunya yang sempat saya temui
kemarin pagi, dari hari ke hari, kondisi kesehatan Yani terus memburuk.
Saya
terbatuk. Pak Roy menoleh. “Kenapa Nona? Jika anda kurang sehat, sebaiknya
pulang saja. Toh sudah berjam-jam kita di sini, apa yang kita tunggu tak juga
datang.”
Entah
kenapa, saya menangkap nada pengusiran halus dari ucapan Pak Roy. Saya
menggeleng. “Anda tak perlu mengkhawatirkan saya, Pak. Tetapi, untuk anda
ketahui, kabut asap ini baru saja menelan satu korban lagi.”
**********
Jenazah
Yani telah dibaringkan di ruang tamu rumahnya saat saya dan Bim Bim datang
melayat. Sehelai kain putih transparan menutupi wajahnya. Samar terlihat wajah
bocah itu yang begitu damai, seakan-akan dia sedang tertidur saja. Di
sekelilingnya, suara isak tangis terdengar serupa gumam yang beruntun. Saya tak
melihat ibunya. Seorang kerabatnya bilang, wanita itu shock berat dan tak ingin ditemui siapapun.
Serombongan
lelaki berseragam tampak menghampiri ayah Yani. Satu darinya memeluk lelaki itu
seraya mengulurkan amplop putih. Lelaki yang tengah berduka itu menggelengkan
kepala, namun ia tampak terlalu letih untuk menyingkirkan tangan yang menyelipkan
amplop itu ke saku baju kokonya.
Pemandangan
barusan tak urung membuat bibir saya terangkat separuh. Berapapun lembar yang
ada di dalam amplop itu, tak akan mampu mengembalikan lagi sosok Yani dan
senyum cerianya ke dunia.
Ponsel
saya berbunyi. Dahi saya berkerut melihat nama Bim Bim. Saya luput menyadari
kapan Bim Bim keluar dari rumah Yani. Saya mendekatkan ponsel ke telinga sambil
menjulurkan leher. Lumayan sulit ternyata, menemukan pria itu di tengah-tengah
puluhan pelayat yang menutup separuh wajah mereka dengan masker.
“Kamu di mana, Bim?”
“Di luar.
Arah jam tiga dekat mobil ambulans.”
“Sebentar.”
Saya
segera keluar setelah menyalami para pelayat yang mulai memenuhi ruang tamu. Bersama
Bim Bim, saya ditugaskan Pak Haris untuk meliput peristiwa pembakaran hutan dan
kabut asap yang terjadi di Riau. Rata-rata rekan kami berkeberatan menjalankan titah
pimpinan redaksi Mercusuar itu. Alasan mereka kurang lebih sama. Lebih baik
meliput peristiwa pasca banjir bandang atau tanah longsor ketimbang pembakaran
hutan. Betapapun mengerikannya, bencana yang lain tidak membuat mereka menderita
sesak napas.
“Ada
apa, Bim?” Saya menghampiri Bim Bim yang berdiri membelakangi mobil ambulans.
“Ada
kabar terbaru. APSI2) akan mendatangi kantor Gubernur besok pagi. Mereka
akan menuntut pemerintah atas pembekuan izin perusahaan sawit yang tergabung
dalam asosiasi.”
“Oh
ya?” Saya melangkah menepi saat beberapa orang pria melewati kami sambil menggotong
keranda. Sepertinya, jenazah Yani akan segera diberangkatkan ke tempat
peristirahatannya yang terakhir.
“Tinggi
juga sinyalmu. Aku malah belum dengar.”
“Ini
memang info tertutup. Asosiasi itu akan datang sekitar pukul sepuluh. Kita
ketemu di kantor Gubernur sekitar pukul sembilan ya.”
“Oke.”
Tak
ada lagi pembicaraan diantara kami saat dari dalam rumah, para pelayat tampak mulai
berdiri dan mengatur saf, bersiap menunaikan shalat jenazah.
***************
Singapura, Agustus 2015
Lelaki
itu menatap gedung-gedung pencakar langit dari balik gorden kamar hotel.
Tangannya menggenggam erat tangkai cangkir, mendekatkan ke bibirnya lalu
menghirup kopinya perlahan-lahan. Srluppp......nikmat!
Di
luar, cakrawala tampak tertutup kabut. Namun tak ada yang perlu ia khawatirkan.
Kadar ISPU di negeri ini belum memasuki level berbahaya. Pun sejak seminggu
lalu, pemerintah negeri ini telah membagikan jutaan masker berkualitas dan
menyiagakan helikopter. Kapan saja diperlukan, capung-capung raksasa itu siap melakukan
tugasnya memancing hujan ataupun melakukan water
bombing.
Teringat
sesuatu, lelaki itu meraih ponselnya.
“Halo.
Selamat pagi, Pak.” Lawan bicaranya menyapanya terlebih dahulu.
“Selamat
pagi. Bagaimana di sana? Aman?”
“Sejauh
ini....aman, Pak. Beberapa media memang cukup nyaring. Tetapi belum sampai mengganggu.”
“Awasi
semuanya. Termasuk yang tidak diperhitungkan sekalipun. Kau mengerti?”
“Mengerti,
Pak.”
“Bagus.”
Lelaki
itu menyimpan ponselnya dan kembali menghirup kopinya. Merasakan kehangatan
cairan hitam pekat itu mengaliri tenggorokan dan melapangkan rongga dadanya
saat bernapas. Rasa lapang itu, telah sebulan ini tak lagi dinikmati jutaan
penduduk di negerinya. Negeri dengan beberapa wilayahnya kini tengah berkemul asap
tebal.
************
Pekanbaru, Agustus 2015
Bim
Bim ternyata tidak bohong. Saat kami mendatangi kantor Gubernur, belasan
jurnalis dari media yang berbeda telah berkumpul di lobi, sebagiannya lagi di
kantin. Situasi udara hari ini tak jauh berbeda dengan kemarin, asap tebal
masih sedemikian pekatnya, dan matahari masih enggan menampakkan sinarnya.
Pukul
sepuluh tiga puluh rombongan asosiasi itu tiba. Jumlah mereka lima orang. Semuanya
berpenampilan rapi dan berdasi. Wajah mereka tertutup oleh masker N95. Tampak
mencolok diantara para pegawai pemerintah dan jurnalis yang rata-rata hanya
berlindung dibalik masker hijau seribu rupiah.
Tanpa
bicara apa-apa dan dengan langkah bergegas, mereka langsung menuju ruang rapat.
Seorang pegawai humas segera menutup pintu dan memberi isyarat pada kami agar
menunggu di luar.
Arloji
saya menunjukkan pukul satu siang saat pintu ruang rapat itu kembali terbuka.
Rombongan pria berdasi keluar. Wajah mereka kini terlihat jelas dengan masker masing-masing
yang telah dilepas.
“Saya
minta, apa yang saya sampaikan ini tidak diinterpretasikan berbeda atau ditulis
sepotong-sepotong.” Satu dari kelima pria ini mulai bicara. Dia menyebut
dirinya sebagai pengacara yang mewakili asosiasi.
“Kalian pasti sudah tahu, bahwa sebagian besar
titik api disinyalir berasal dari lahan konsesi perusahaan sawit. Tetapi, satu
hal yang perlu kalian pahami, bahwa lahan itu belum dikuasai oleh perusahaan. Kesimpulannya,
lahan yang terbakar adalah milik masyarakat. Dan pelaku pembakaran juga adalah
masyarakat sendiri yang ingin membuka lahan. Meski begitu, perusahaan tetap
menunjukkan tanggungjawabnya dengan membantu proses pemadaman. Pihak perusahaan
juga sudah melaporkan ke aparat. Dari sisi
regulasi dan standard of procedure,
semua upaya yang ditempuh perusahaan sudah benar. Yang kami persoalkan
sekarang, mengapa izin mereka malah dibekukan?” Pertanyaan pria itu terucap
lantang.
“Apa
perusahaan tidak melarang masyarakat untuk membakar hutan, Pak? Bukankah lahan
itu tetap masuk kawasan perusahaan meski secara hak masih milik masyarakat?” Seorang
jurnalis sigap bertanya.
“Perusahaan
bisa saja melakukannya, tetapi dalam prakteknya tak semudah yang anda
bayangkan. Apalagi, regulasi juga memperbolehkan masyarakat membakar hutan kok. Tetapi dengan batas-batas tertentu.
Silakan anda baca Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup jika anda tidak percaya.”
Saya
mengabaikan nada tegas pria ini dengan ikut bertanya, “Boleh saya tahu wilayah
mana saja yang termasuk dalam tuntutan APSI, Pak?”
Dia menoleh
pada saya, lalu mengerutkan dahinya, tampak serius mengingat-ingat. “Yang
terbanyak di Kecamatan Tampan, lalu Kecamatan Bukit Raya, terakhir Payung
Sekaki.”
Saya
mencatatnya baik-baik. Pertanyaan demi pertanyaan masih susul menyusul di
sekeliling saya, namun pikiran saya sudah terbang jauh. Nama-nama yang baru disebutkan
itu, dalam sekejap sontak mengingatkan saya pada sesuatu.
*******************
Pukul
enam tiga puluh. Pagi masih muda. Namun langit telah terpulas warna abu-abu. Sungguh,
saya mulai merindukan sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela kost-kostan
setiap saya terbangun kesiangan. Namun tugas saya belum selesai. Dan saya telah
berjanji akan melakukan yang terbaik.
Tak
sanggup saya bayangkan apa akan terjadi di masa depan, jika di masa sekarang
saja, dampak pembakaran hutan ini sudah menjadi yang terparah dalam kurun waktu
delapan belas tahun. Ya. 18 tahun! Tak perlulah kau terkejut begitu. Nyatanya, pengrusakan
ini memang sudah terjadi sejak saya mulai diajarkan untuk mencintai lingkungan,
di bangku sekolah dasar dulu. Tuhan memang sangat pemurah, mengulur waktu begitu
panjangnya agar hambaNya menyadari bencana besar apa yang bakal mereka tuai.
Saya
kembali membasahi masker dengan air mineral. Entah sudah berapa lusin masker saya
habiskan dalam sebulan terakhir. Dan ini entah pagi yang keberapa ummi menelpon,
menyuruh saya untuk segera kembali ke Jakarta. Mengingatkan saya pada janji
bahwa ini adalah tugas terakhir saya di Pekanbaru.
“Retni,
kamu di sana baik-baik saja ‘kan? Bagaimana peliputanmu? Jangan tunggu
paru-parumu menghitam dulu ye baru
kamu pulang. Bulan depan itu proses lamaran kamu. Nggak lucu ‘kan kalau pertunangan
kalian harus ditunda sampai tahun depan karena calon mempelai wanitanya kena
ISPA?”
Saya
tertawa. Kalimat ummi terdengar lucu meski saya yakin dia benar-benar cemas.
“Alhamdulillah,
saya masih bernapas kok, Mi. Sudah hampir selesai. Insya Allah, awal bulan
depan saya pulang.”
“Kamu
masak sendiri ‘kan? Nggak jajan di luar mulu?”
“Iya,
Ummi.” Saya tidak berbohong. Saya memang jarang makan di luar. Namun apa yang biasa
saya masak di dapur kost-kostan tak lebih dari mi instan dan telur ceplok.
“Kamu
masih inget cerita kepiting didandanin ‘kan, Ret?”
“Masih,
Ummi.” Saya menjawab pelan. Saya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Dulu,
ummi sering bercerita tentang mertua yang membawakan kepiting untuk menantu
perempuannya. Sang mertua berkata, tolong
ini kepiting didandanin. Dan sang menantu yang sama sekali tak bisa memasak,
ternyata benar-benar mendandani kepiting itu dengan membedaki, memberinya gincu
dan juga pita.
Ini
adalah dongeng orang-orang tua Betawi untuk mengingatkan anak gadisnya, bahwa
saat berumah tangga, tidak boleh tidak, mereka harus pintar memasak. Meski
tulisan saya tersebar di puluhan edisi Mercusuar dan beberapa media lainnya, di
mata ummi, semua itu tak ada artinya jika mengulek sambal pun saya tidak becus.
“Arul
pernah menelpon kagak?”
“Pernah,
Mi. Dua kali. Tetapi, dia tidak terlalu cemas kok.” Saya menjawab dengan senyum. Saya dan Arul – calon suami saya
itu -dijodohkan dengan cara ngedelengin3).
Waktu
itu, Encing Noni datang ke rumah dan mengenalkan sosok Arul secara tertulis pada saya, Ummi dan juga
Abah. Encing Noni yang juga sepupu ummi, datang bersama dua lembar kertas HVS
berisi biodata Arul berikut selembar fotonya yang tengah berpose di depan
menara Eiffel. Encing lalu meminta pada ummi dan abah agar saya melakukan hal
yang sama. Ummi dan abah tak keberatan. Meski sehari saja berpisah dari gadget
membuat mereka seakan kehilangan dompet beserta seluruh isinya, di lain sisi, ummi
dan abah tetaplah orang Betawi tempo doeloe yang setia pada tradisi.
Termasuk tradisi yang buat saya sudah ketinggalan jaman seperti ngedelengin sekalipun.
Demi
menghormati Encing, saya melakukan juga apa yang dia inginkan. Saya janjian
bertemu Arul dua minggu kemudian. Bukan di bioskop ataupun restoran romantis.
Melainkan pada acara penyerahan penghargaan blogger traveller terbaik di mana Arul menjadi salah satu pemenangnya. Arul seorang
penulis dan blogger traveller papan
atas dengan tarif per artikelnya sudah mencapai angka enam digit.
Tetapi,
sungguh, bukan enam digit itu yang membuat saya tertarik. Pertama, karena secara
fisik, Arul lumayan tampan dan menarik. Wajahnya seperti aktor-aktor drama
Turki yang setiap malam wara-wiri di salah satu teve swasta. Kedua, karena kami
punya passion yang sama. Saya membayangkan, setelah menikah nanti, saya
dan Arul akan pergi mengunjungi tempat-tempat indah di berbagai belahan dunia,
menulis kisah perjalanan kami dan mendokumentasikan semua kenangan yang
terjejak. Dan ketiga, karena saya baru patah hati. Alasan terakhir inilah,
sepertinya yang paling kuat mendorong saya untuk menerima Arul meski bilangan
pertemuan saya dengannya masih minim.
Patah
hati juga sepertinya bukan istilah yang tepat. Toh antara saya dan dia tidak pernah menjalin hubungan yang
spesial. Tetapi saya dan dia juga sama-sama menyadari kalau perasaan kami
saling terikat. Dan saat ikatan itu harus terburai, tiba-tiba saja saya merasa
seperti ada lubang besar di dalam jiwa saya.
Entahlah.
Saya juga tidak tahu apakah keputusan ini benar-benar dapat menyembuhkan luka.
Satu yang pasti, saya benci lelaki yang tidak bisa meyakinkan saya bahwa
hubungan kami pada akhirnya akan menuju satu titik. Saya benci lelaki yang
diam-diam bertunangan tanpa pernah mengabari saya kenapa dia akhirnya sampai pada
keputusan mendadak itu.
Saya
menyalakan laptop dan mengetik ulang semua catatan dari konferensi pers singkat
bersama Yudi Atmadja, nama pengacara yang dibayar oleh asosiasi pengusaha itu. Saya
juga membuka kembali folder berisi file-file kasus ganti rugi lahan oleh
perusahaan sawit. Masyarakat menghendaki ganti rugi yang sesuai harga tanah. Namun
perusahaan bersikukuh hanya mengganti sepersepuluh dari harga itu. Disertai janji
manis untuk memprioritaskan masyarakat setempat dalam perekrutan karyawan dan
setiap tahunnya akan memperoleh bantuan CSR. Persoalan itu akhirnya selesai dengan
kemenangan pada pihak perusahaan.
Sesaat,
kening saya berkerut. Bagaimana mungkin Yudi Atmadja bersikukuh kalau lahan
pembakaran itu adalah milik masyarakat sedangkan semua bukti jelas-jelas menunjukkan
kalau lahan telah dikuasai oleh perusahaan?
Saya
meraih ponsel, mengetik pesan dan mengirimkannya pada Bim Bim. Besok kita ke Tampan. Ada kejanggalan dari
pembebasan lahan oleh perusahaan X. Kita akan bertemu seseorang di sana.
************
“Cari
siapo?”
Perempuan
yang membuka pintu rumah sederhana itu menatap saya dan Bim Bim dengan tatapan curiga.
Saya menurunkan masker, tersenyum sambil mengulurkan tangan.
“Saya
Retni. Ini masih rumah Pak Amrialis ‘kan? Saya ingin bertemu beliau. Katakan
saja Retni dari Mercusuar. Bapak pasti tahu.”
“Tunggu
sebentar.”
Perempuan
itu masuk setelah terlebih dulu menutup pintu. Bim Bim menatap saya dengan alis
bertaut dan sinar mata keheranan.
“Kenapa
dia melihat kita seperti itu? Apa dipikirnya kita akan merampok atau menipu?”
Saya
mengedik bahu. “Kita akan tahu sebentar lagi.”
Butuh
lima menit menunggu sampai pintu kayu itu berderit dan kembali terbuka. Kali
ini perempuan itu tak sendirian. Seorang pria dengan kening dan sudut mata
berkedut, berjalan di belakangnya dengan tubuh sedikit terbungkuk.
“Pak
Amrialis?” Saya lebih dulu menyapanya. Tiga tahun berlalu, pria berusia enam
puluhan tahun ini terlihat jauh lebih kurus. Hanya saja, dari caranya memandang
saya, sepertinya dia mengalami gangguan penglihatan, atau mungkin juga sedikit
lupa.
“Kamu
Retni?” Dia mengacungkan telunjuknya seraya menajamkan matanya. Saya mengangguk
dan tersenyum. “Benar, Pak. Kita dulu sama-sama makan ubi rebus di teras ini.
Ubi yang baru bapak cabut dari kebun belakang.”
Pak Amrialis
terbelalak. “Astagfirullah, maaf nak. Beno-beno4)
lupo saya tadi. Ayo, ayo masuk. Ajak temanmu. Siapo namo?”
Bim
Bim memperkenalkan dirinya. Kami lalu duduk di ruang tamu yang berisi
seperangkat sofa dengan sobekan lebar menganga di sana sini hingga lapisan busa
di dalamnya terlihat jelas.
“Maaf,
nak. Sudah tiga tahun, rumah Bapak justru tambah jelek.” Pak Amrialis tertawa
kecil. “Yang tadi itu keponakan saya. Bapaknyo
tempo hari ditangkap polisi, menyusul teman-temannyo yang lain. Jadi setiap kali ada orang datang, dia sudah curiga
duluan.”
“Ditangkap
kenapa, Pak?”
Pak Amrialis
menghela napas. “Mereka membakar hutan. Disuruh orang sawit. Awalnya mereka juga ndak mau, tetapi perusahaan janji akan membantu mereka kalau sampai
tertangkap.”
“Hm.
Tetap saja orang kecil yang jadi tumbal. Kenapa yang menyuruh malah tidak
ditangkap?” Saya mendengus gusar. Nyatanya kegeraman saya itu tak lebih dari
pertanyaan retoris belaka. Sejak dulu sampai sekarang, pihak perusahaan seakan terlindungi
oleh tameng kebal hukum yang berlapis-lapis. Peluru pasal demi pasal atas
tindak pengrusakan lingkungan seakan langsung memantul kembali atau jatuh ke
tanah saat coba ditembakkan ke arah mereka. “Tentang lahan yang dulu itu, bagaimana kelanjutannya,
Pak? Saya minta maaf, waktu itu tidak ikut mendampingi sampai selesai.” Ucap
saya sedikit menyesal. [bersambung]




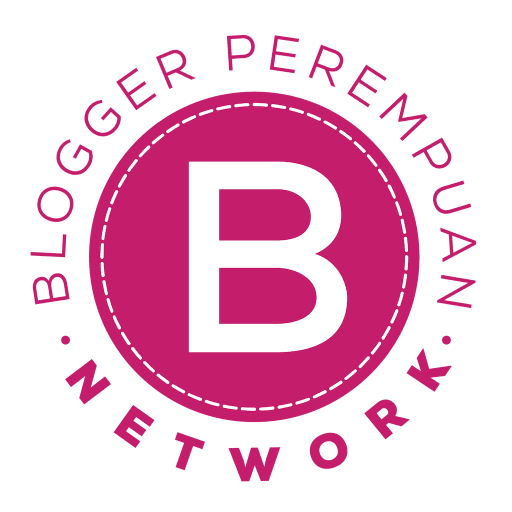










Eh ada namaku hehehe. suka kali baca tulisan nya kak ria ini bagus bagus jadi pengen belajar nulis ah
ReplyDeleteIya roy jadi figuran hehe
DeleteCeritanya bagus, mbak :)
ReplyDeleteIni ceritanya ya apa yang terjadi di sekitar..
kutunggu lanjutannyaaaaa...
Okeey insya Allah
DeleteSaya suka banget baca cerpen. pasti seru nih lanjutannya.
ReplyDeletePenulisan sudut pandang orang pertama, pake bahasa 'saya-kamu' bukan 'aku-kamu', jarang bisa nikmati karena bahasanya biasanya pasti baku. Tapi khusus yang ini lancar jaya. Luwes ae kesannya. Like it....
ReplyDeleteLanjuuuttt....
Ini pertama kali saya nyoba pake pov 'saya'. Makasih..
DeleteKeren kak, lanjutkan.
ReplyDeleteOkey insya Allah
DeleteNice story kak.... masalah yang diangkat lumayan berat, tapi bisa mengalir dengan lancar dan enak...
ReplyDeleteIya latarnya ttg lingkungan
Deletecerita yang bagus,,di tunggu selanjutnya
ReplyDeleteOkey..
Deletebagus banget mbak. aku jadi belajar nulis cerpen dan novel. ini jadi referensi aku belajar :D
ReplyDeleteWah makasiih. .
DeleteAduuuh terhanyut banget bacanya dari awal hingga akhir.. tak terasa sudah abis aja bacanya.. Lanjutannya pleaseeee kak Ria.. :))
ReplyDeleteKomen perdana di blognya kak Ria neh and i love it. :) bakal sering2 buka blog ini neh.
Semoga betah berkunjung yaa hehe
DeleteWah cerita berlatar fakta sepertinya :)
ReplyDeleteIya benar
DeleteSeneng bisa baca cerpen lagi, di tunggu kelanjutannya kak
ReplyDeleteSiiip
Deleteduh, saya sempat merasakan sendiri efeknya waktu masih tinggal di Pekanbaru. Baca cerbungnya kakak bikin hati ikut gremet-gremet :( ditunggu part 2nya
ReplyDeleteOkeey
Deletewahh seneng banget baca cerpennya kak ria, mengalir dan dapet info tentang msalah pekanbaru ini. btw baca cerpen kak ria ttg korban aku jadi inget almarhum ibu temenku yang jadi salah satu korban asap, kena ISPA. setidaknya aku tau bahwa bahayanya luar biasa
ReplyDeleteIya choty. Apalagi jika anak2 dan manula yg kena. Bisa fatal
DeleteEaaaa bersambung... :D Lagi seru pun...
ReplyDeleteYa iyalaah panjang pun...
Delete