Bertepatan Hari Guru Nasional, saya ingin meresensi sebuah kisah nyata tentang
sosok mahaguru dalam kehidupan Mitch Albom, penulis yang dalam tiga bulan
terakhir (karya-karyanya) sukses mencuri hati dan minat saya.
Dalam kisah ini, Mitch bercerita tentang kesempatan keduanya bertemu
kembali dengan mantan dosennya, Morrie Schwartz, pada bulan-bulan terakhir
kehidupannya. Morrie terkena penyakit ALS (amyotrophic lateral sclerosis),
sebuah penyakit ganas yang menyerang system saraf dan belum ditemukan obatnya
pada masa itu (tahun 1994).
Pada pertemuan-pertemuan yang berlangsung di rumah Morrie setiap hari
Selasa dalam kondisi sang dosen yang kian tak berdaya itulah,
Mitch memperoleh banyak pelajaran tentang hidup : tentang dunia, penyesalan,
keluarga, kematian, uang, cinta, budaya dan sebagainya.
Bagi Mitch, hal-hal yang berkesan darinya tentang Morrie, adalah hal-hal yang pernah diajarkan dosen itu kepadanya tentang "bersikap manusiawi" dan peduli kepada orang lain". (hal. 19).
Membaca karya Mitch yang ketiga ini setelah For One More Day dan 5 People
You Meet in Heaven, saya mulai mengenal pola mainstream dalam tulisan Mitch,
yaitu selalu bersinggungan dengan kematian, orang-orang yang pernah hadir dan
punya arti besar dalam hidup meski disadari atau tidak oleh sang tokoh, juga penceritaan dengan pola alur yang maju mundur. Meski demikian, anehnya,
saya belum juga merasa bosan dan masih ingin terus memburu karya-karya Mitch.
Mungkin, inilah beberapa poin kelebihan yang saya temukan dalam
karya-karya Mitch dan sangat jarang saya temukan dalam karya-karya penulis lain
:
Pertama – Saya tidak tahu seberapa besar Mitch melibatkan emosi dan
perasaannya saat menulis, satu yang pasti, setiap kata yang ditulis Mitch
seakan memiliki kekuatan tak kasat mata yang menahan kita untuk tak buru-buru
menyelesaikannya, sebaliknya berhenti sejenak untuk merenungkan maknanya. Bahkan pada
beberapa titik perhentian, emosi dalam diri saya terbangkitkan begitu saja,
terwujud dalam rasa haru, pedih, keinginan untuk menangis atau bahkan
benar-benar meneteskan air mata.
Kedua – bab demi bab disusun sedemikian efektif, pendek
dan padat, sehingga pembaca selalu terpancing untuk membalik lembar berikutnya.
Mitch juga jarang berlama-lama mengurai kisah flashback yang berpotensi
menimbulkan kejenuhan.
Ketiga – inilah kelebihan utama dari karya Mitch, yaitu selalu sarat
perenungan, hikmah, dan menggugah kesadaran kita akan “pentingnya” menyiapkan
bekal sebelum ajal datang, serta memanfaatkan hidup yang kita jalani saat ini dengan
sebaik-baiknya.
Dan diantara ketiga buku Mitch yang sudah saya baca, buku ini adalah
yang paling banyak “puppy’s ear”nya, atau lipatan-lipatan pada halaman yang
saya jadikan penanda akan kalimat yang menurut saya bagus dan bermakna. Saya memang bukan
pembaca yang baik, jika indikator baik itu adalah mengusahakan agar buku yang
dibaca tetap rapi, mulus seperti baru, kalau perlu disampul plastik agar tak
mudah kotor atau robek. Semakin saya menyukai sebuah buku, maka biasanya semakin
leceklah kondisinya akibat keseringan dibaca, atau dibaca dimana saja hingga
rentan tertindih bantal atau benda lain, juga banyak lipatannya karena saya
tak punya banyak waktu untuk memindahkan kalimat yang ingin saya tandai ke
post-it note ataupun ke dalam buku catatan.
Meskipun karya Mitch yang satu ini adalah sebuah kisah nyata, Mitch tetap tak melupakan
pentingnya pendeskripsian dalam penuturannya hingga kisah ini pun menjelma sama detilnya
dengan fiksi.
Lihatlah bagaimana Mitch menggambarkan kondisi Morrie yang kurus kering
akibat penyakitnya : “Kita dapat melingkarkan jemari kita ke sekeliling pahanya
dan jemari kita dapat saling bertemu. Andaikata ia dapat berdiri, tingginya
tidak akan lebih dari satu setengah meter, dan celana yang pas baginya mungkin
celana anak kelas enam sekolah dasar.” (hal. 51).
Atau saat ia menggambarkan penderitaan yang dialami pasien ALS : “ALS
dapat dipadankan dengan sebatang lilin yang menyala : api membakar sumbunya dan
yang tersisa hanya seonggok lilin. Kita kehilangan kendali atas tubuh hingga
tak mampu duduk tegak lagi. Andai pun masih hidup, dan nyawa masih ada, semua
itu terkungkung dalam tubuh lumpuh, yang hanya mampu berkedip dan berdecak
seperti manusia beku dalam film-film fiksi ilmiah. (hal. 10).
Belumlah lengkap resensi kali ini jika belum menyertakan hasil
lipatan-lipatan saya dari buku Mitch. Berikut diantaranya :
“Yang paling penting dalam hidup adalah belajar cara memberikan cinta
kita, dan membiarkan cinta itu datang.” (hal. 55).
“Sesungguhnyalah, selain keluarga, tidak ada pondasi, tidak ada landasan
kokoh yang memungkinkan manusia bertahan sampai hari ini. Tanpa dukungan, cinta
dan kasih sayang dari keluarga, kita seperti tidak memiliki apapun.” (hal. 97).
“Jangan mengikatkan diri pada kebendaan, karena segala sesuatu tidak
kekal.” (hal. 109).
Dengan segala keistimewaannya, bukan berarti buku ini tak punya kekurangan. Untuk sebuah buku yang telah memasuki cetakan ke-9, buku ini belum
benar-benar bebas typo. Bahkan beberapa repetisi kata yang semula saya duga
adalah typo membuat saya jadi berpikir mana yang benar : eksploatasi atau
eksploitasi, bernadar atau bernazar, fondasi atau pondasi?
Juga bagi anda yang menginginkan “hiburan” dalam makna harfiah dari sebuah
buku, dimana anda terbebas dari kewajiban untuk memikirkan pesan-pesan,
merenung, menganalisa relevansinya dengan perjalanan hidup, mungkin, buat
anda, karya-karya Mitch akan terasa bold and dark.
Namun bagi anda yang ingin memperkaya hati dengan makna-makna kehidupan
dalam jalinan kisah yang dalam dan menyentuh, boleh jadi, karya-karya Mitch
adalah karya yang tepat untuk dijadikan pilihan.
Terakhir, saya ucapkan Selamat Hari Guru untuk semua pendidik di negeri ini.
Jika Mitch Albom memiliki Morrie Schwartz sebagai guru yang sangat berpengaruh
pada kehidupannya dan meninggalkan jejak kebersamaan yang begitu bermakna,
siapa pula gerangan Morrie dalam kehidupan anda?
Judul : Tuesdays with Morrie
Penulis : Mitch Albom
Penerbit :
GPU
Tahun : Juli 2014 (cet-9)
Hal : 209 hal



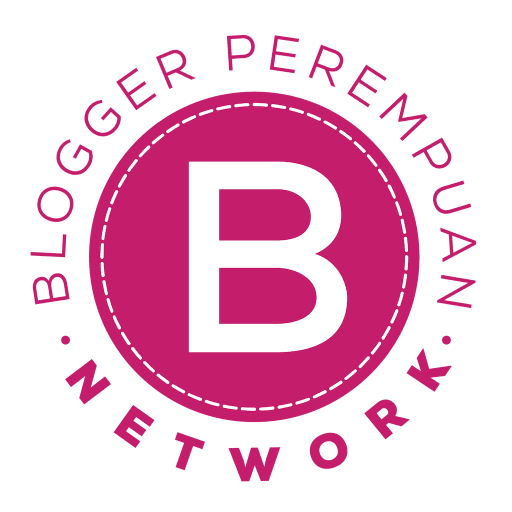










Wah, menarik banget. Saya belum pernah baca novel Mitch Albom. Dan menulis novel sedalam ini pastilah sulit, saya dapat membayangkannya.
ReplyDeleteALS mengingatkanku akan aksi Ice Bucket Challenge yang heboh dilakuin selebriti dunia Agustus lalu. Ternyata, bahkan sampai sekarang belum ditemukan obatnya, dan biaya penelitiannya pun sangat mahal.
ReplyDeleteAku mau punya punya buku-buku Mitch Albom nanti. Aku, seperti yang tertulis di paragraf kedua dari bawah, sangat ingin memperkaya hati dengan makna-makna kehidupan dalam jalinan kisah yang dalam dan menyentuh. :D
aku punya buku Mitch Albom tapi belum sempet baca.. huhuu..
ReplyDeleteabis baca resensi ini jadi beneran kepingin..
Belum sekali pun baca karya Mitch, dan dengan peringatan di bawah resensi ini, sepertinya ini tipe buku yang lama akan kuselesaikan bacanya hehehe.....
ReplyDeleteMelani : iya, sepertinya karya2 mitch bukan hasil proses yg instan
ReplyDeleteIya mbak eky, cara Mitch menggambarkan penderitaan gurunya disini bikin nyesekk, parah bgt efek penyakit itu
ReplyDeleteMbak linda : nunggu resensi mbak kalo udah baca:-)
ReplyDeleteLeyla : dicoba aja 1, x aja klik, buktinya sama kaliluna yg kalimatnya panjang2 bisa suka :D
ReplyDeleteSaya sudah lebih dulu jatuh cinta pada karya Mitch Albom sebelum mengenal Tere Liye. Saya selalu berhasil dibuat merenung tentang hal-hal yang simple dan bahkan terlupakan saat membaca karya dia.
ReplyDeleteAku juga suka baca Mitch Albom...tergolong berat untuk sekedar hiburan tapi sarat makna untuk perenungan.
ReplyDeleteJika ditanya siapa sosok Morrie dlm hidupku..tentu Ayah Ibuku...seperti yang Mitch katakan..tanpa keluarga kita bukan siapa siapa.
Aku blm punya buku ini..semoga nemu mksh kak Lyta...