Gleneagles Hospital, Singapura, Maret 1985
Wanita dengan
tunik panjang hijau muda berselubung selimut bercorak garis itu rebah di brankar
beroda. Posisi tubuhnya empat puluh lima derajat, kepala bersangga sebuah
bantal tipis, dan kedua matanya menatap hampa pada dinding di hadapannya yang nyaris
sama kosongnya. Rambut panjangnya tergerai begitu saja, kusut masai, menyebar
di atas bantal seperti surai singa, dan dengan ekspresinya saat ini, bindi[1]
merah pada keningnya justru menunjukkan kombinasi yang tampak menakutkan.
Di dalam
ruangan kamar itu, hanya ada televisi yang tidak dihidupkan. Tembok polos putih
bersih membentang dari sisi jendela hingga pintu masuk, berbatas partisi berlapis
tirai biru yang terhubung dengan ruang yang dilengkapi sofa, seakan memberi
privasi untuk kenyamanan si pasien dari pengunjung yang datang membesuk.
Namun tak ada yang tahu apakah saat ini dia sudah merasa nyaman atau sebaliknya. Slang infus dari botol berisi cairan bening masih terhubung ke pembuluh darah di pangkal pergelangan tangannya. Menetes teratur, seperti embun
yang menetes dari pucuk dedaunan, menyuplai energi dan vitamin ke dalam tubuhnya
yang mengalir bersama aliran darah. Tampak pula balutan perban menutupi
pergelangan tangan yang sebelah lagi, menyembunyikan goresan luka yang ia
torehkan sendiri beberapa jam yang lalu. Torehan itu cukup dalam, membuatnya
banyak kehilangan darah yang mengalir deras dari urat venanya yang terputus.
Dan, ia melakukannya setelah mengira bahwa perbuatannya sebelum itu saat
mencelakakan seorang bocah kecil telah berhasil mengantarkan roh bocah itu ke
langit. Bocah yang tak lain adalah putranya sendiri.
“Sayang, kau sudah
sadar?”
Pria dengan
raut wajah muram menghampiri sisi brankar. Ia menatap wanita itu dengan
ekspresi pedih, getir sekaligus iba. Mata abu-abunya tampak kelam. Dan
hidungnya yang membengkok sedikit dironai warna kemerahan. Ia memang telah
mengeluarkan banyak air mata sejak beberapa jam lalu. Air mata cemas dan
kepedihan yang hanya ia sendiri yang mampu mendeskripsikan seberapa dalamnya.
“Di mana
anakku?”
Pertanyaan
itu meluncur dari bibir sang wanita yang sedikit membiru. Nyaris tanpa
ekspresi. Seakan dia baru saja bertanya apakah seseorang berhasil menemukan
brosnya yang hilang.
“Woh achha hoon (Dia baik-baik saja).
Sekarang ada bersama bibinya. Bagaimana denganmu, Sayang?”
Wanita itu
tak menyahut. Bahkan ia enggan untuk sekadar menoleh pada pria yang tak lain
adalah suaminya sendiri. Pria malang itu tak perlu tahu, dan mungkin tak akan
mengerti, bahwa semua kegilaan yang terjadi pagi tadi, semua itu bergerak di
luar kesadarannya. Melampaui batas kendalinya. Mengalahkan akal sehatnya.
“Aku ingin
memberitahumu sesuatu.” Bibirnya bergetar saat akhirnya ia menggerakkan
kepalanya. Lalu menatap tepat ke manik mata suaminya.
“Katakan
saja, mere pyaara (cintaku). Aku di
sini. Mendengarmu.” Pria itu menarik kursinya lebih dekat ke brankar istrinya.
“Aku sangat
menyayangi mereka.” Wanita itu mulai bicara. “Aku tidak ingin mereka terluka
dan disakiti. Aku tidak rela jika ada orang yang berniat buruk pada mereka.”
Seraya
mengatakan itu, air matanya mulai mengalir, meluncur membasahi pelipis, jatuh
pada alas bantal yang menyangga kepalanya.
“Jika
sesuatu yang buruk mengancam mereka lagi, lebih baik aku mengantarkan mereka ke
tempat yang aman. Tempat di mana mereka tak mungkin lagi tersakiti.”
Raut wajah pria
itu spontan menegang. “Sayang, apa yang kau maksud dengan tempat yang aman?
Tolong, jangan katakan bahwa kau mendengar lagi bisikan yang menyuruhmu untuk...”
Ucapan pria itu terhenti. Ia terlalu ngeri saat membayangkan kelanjutan
kalimatnya sendiri.
Wanita itu menggeleng.
Tatapannya masih sama nanarnya. Air mata kian menggenangi kedua rongga matanya
yang besar. “Mujhe maaf kardijiye
(Maafkan aku). Aku berjanji tidak akan mengulang ketololan itu lagi. Tapi
kumohon, berjanjilah padaku.”
“Janji apa,
Sayang? Katakanlah, apa pun itu, aku akan berusaha memenuhinya.”
Wanita itu menggerakkan sebelah tangannya yang
terbalut perban. Memahami isyarat itu, sang suami meraih jemarinya,
menggenggamnya perlahan-lahan.
“Aku ingin
mereka bahagia. Dan hanya aku yang tahu, kebahagiaan macam apa yang pantas untuk
mereka. Jadi, berilah aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Jangan pernah membohongiku,
apalagi menghina apa pun yang kulakukan.”
Pria itu mengangguk
ragu. Menyadari betapa rapuhnya wanita yang ia nikahi tujuh tahun lalu itu.
Wanita yang telah melalui banyak trauma di sepanjang masa kecilnya, trauma yang
ternyata berdampak buruk pada kekuatan mentalnya kini. Sedikit saja masalah,
sudah cukup untuk membuatnya banjir air mata dan mengalami depresi. Bahkan juga
melakukan kenekatan tak terduga.
“ Aku
berjanji, Sayang. Aku berjanji. Sekarang, beristirahatlah. Aku akan tetap di sini.
Menemanimu.”
Wanita itu akhirnya memejamkan mata. Sebelah tangannya yang terbalut perban masih berada dalam genggaman erat sang suami. Sesekali denyut perih dari torehan luka itu masih terasa, sebagaimana
luka yang pernah tertoreh sangat dalam di hatinya. Luka lama yang belum juga
mengering.
[1]
Bindi: sebuah tanda di
kening seorang wanita yang sudah menikah yang dalam kebudayaan India (Hindu)
merupakan simbol kesetiaannya kepada suaminya.



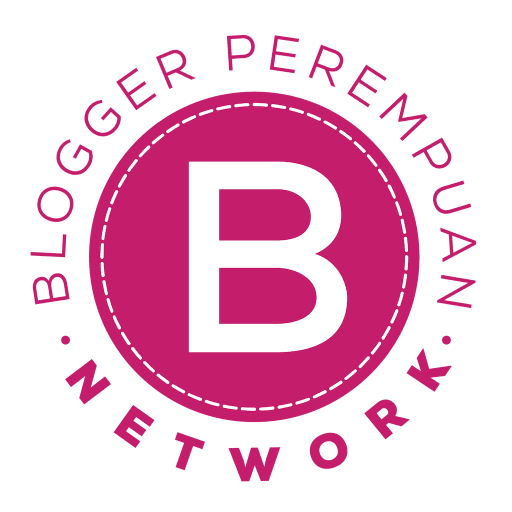










Mbaaak...merinding saya.
ReplyDeleteEh baca bindi langsung lamat2 ada suara musik India, sambil membayangkan orang2nya...:)
Menunggu pak pos juga di depan pintu.
Semoga laris manis dan membawa kebaikan untuk penulis, pembaca dan penerbit.aamiin
Amiin. Makasiih, semoga Betang juga laris manis n bawa kebaikan untuk semua :D
ReplyDeleteBaca prolog ini bikin penasaraaaan euy :D
ReplyDeletepenasaraaaannnnn... sukses selalu ya Mbak Lyta. Laris manisss, aamiin...
ReplyDeleteMakasih mbak Eky, mbak Ary, nanti dibeli yaa :D
ReplyDeletekeknya ini keren..... aku pesan ya mba. kalu udah ada kabarin ya:)
ReplyDeletepengen baca ^_^
ReplyDelete